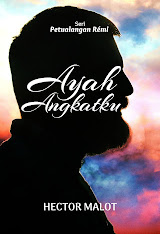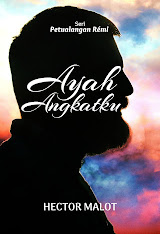

 Aku tak pernah berpikir banyak apa itu ayah. Samar-samar aku tadinya membayangkan dia seperti seorang ibu bersuara besar, tapi saat memandang orang ini yang jatuh dari langit, aku merasa sangat cemas dan takut.
Aku tak pernah berpikir banyak apa itu ayah. Samar-samar aku tadinya membayangkan dia seperti seorang ibu bersuara besar, tapi saat memandang orang ini yang jatuh dari langit, aku merasa sangat cemas dan takut.
Aku menghampiri untuk giliran memeluk pria itu, tapi dia mencegatku dengan ujung tongkatnya:
“Siapa ini?”
“Ini Rémi.”
“Kau sudah bilang...”
“
Well, ya, tapi...itu tidak benar, karena...”
“Alah! Tidak benar, tidak benar.”
Dia melangkah ke arahku dengan tongkat teracung; sontak aku menciut mundur.
Apa yang kuperbuat? Apa salahku? Kenapa sambutannya begitu padahal aku cuma ingin memeluknya.
Aku tak sempat menimbang berbagai pertanyaan ini yang menghimpit benakku yang kesusahan.
“Jadi kau sedang merayakan Selasa Gemuk,” katanya. “Senang rasanya, karena aku kelaparan. Ada makanan apa untuk makan malam?”
“Aku sedang membuat panekuk.”
“Aku bisa lihat, tapi kau tak mungkin menyediakan panekuk untuk seseorang yang sudah menempuh jarak bermil-mil sepertiku.”
“Aku tak punya makanan lain. Kau tahu kami tidak mengira kau akan datang.”
“Apa? Tak ada makanan lain! Tak ada makanan untuk makan malam!” Dia menengok sekeliling dapur.
“Itu ada mentega.”
Dia mendongak ke langit-langit, ke titik di mana bakon biasa bergantung, tapi sudah lama tak ada apa-apa pada kaitnya; hanya beberapa ikat bawang merah dan bawang putih tergelantung dari tiangnya sekarang.
“Ini beberapa bawang merah,” ujarnya, menggetok turun seikat bawang merah dengan tongkat besarnya. “Dengan empat atau lima siung bawang merah dan sepotong mentega kita akan punya sup enak. Angkat panekuknya dan panggang bawang-bawang ini di panci!”
“Angkat panekuknya dari wajan!” Bu Barberin tidak menjawab. Dia justru bergegas menuruti permintaan suaminya selagi pria itu duduk di sebuah kursi di sudut perapian.
Aku tak berani beranjak dari tempat di mana tongkatnya mendorongku. Bersandar ke meja, aku menatapnya.
Dia pria lima puluhan dengan wajah keras dan adat kasar. Kepalanya miring sedikit ke bahu kanan, gara-gara luka yang dia dapat, dan kecacatan ini memberinya roman yang lebih menakutkan lagi.
Bu Barberin sudah menaruh wajan kembali di atas api.
“Apa dengan mentega sesedikit itu kau akan membuat sup?” tanyanya.
Maka dia merenggut piring berisi mentega dan memasukkan semuanya ke dalam panci.
Tak ada lagi mentega...berarti...tak ada lagi panekuk.
Di waktu lain aku pasti sudah kecewa berat dengan bencana ini, tapi aku tidak sedang memikirkan panekuk dan gorengan apel sekarang. Pikiran yang paling penting dalam kepalaku sekarang adalah bahwa pria yang terasa begitu kejam ini adalah ayahku!
“Ayahku, ayahku!” Itu kata yang kuulang-ulang pada diriku sendiri sambil melamun.
Aku tak pernah berpikir banyak apa itu ayah. Samar-samar aku tadinya membayangkan dia seperti seorang ibu bersuara besar, tapi saat memandang orang ini yang jatuh dari langit, aku merasa sangat cemas dan takut.
Aku ingin memeluknya dan dia justru mendorongku dengan tongkatnya. Kenapa? Ibuku tak pernah mendorongku saat aku menghampiri untuk memeluknya; sebaliknya, dia selalu merangkul dan mendekapku erat.
“Daripada diam begitu seperti beku,” katanya, “cepat tempatkan piring-piring di meja.”
Aku nyaris jatuh saat buru-buru menurutinya. Sup sudah jadi. Bu Barberin menghidangkannya di atas piring-piring.
Kemudian, beranjak dari pojok cerobong besar, dia datang dan duduk di meja dan mulai makan, hanya berhenti dari waktu ke waktu untuk memandangku sepintas.