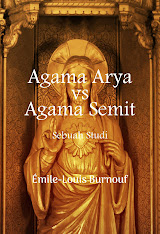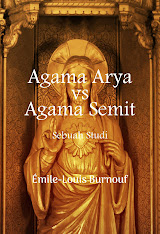
 Sains telah membuktikan bahwa tendensi asli bangsa-bangsa Arya adalah Panteisme, sementara Monoteisme, adalah doktrin tetap bangsa-bangsa Semitik. Panteisme dan Monoteisme adalah sungguh kanal besar di mana kedua sungai suci umat manusia mengalir.
Sains telah membuktikan bahwa tendensi asli bangsa-bangsa Arya adalah Panteisme, sementara Monoteisme, adalah doktrin tetap bangsa-bangsa Semitik. Panteisme dan Monoteisme adalah sungguh kanal besar di mana kedua sungai suci umat manusia mengalir.
Saat menelusuri sejarah agama-agama, sesuai tuntutan metode, kita melihat bahwa penerapan prinsip-prinsip dogmatis pada perilaku hidup merupakan fakta belakangan, yang mencirikan pendatang-pendatang terakhir di antara agama-agama—agama Muhammad, agama Kristus, dan agama Buddha.
Di dalam al-Qur’an, metafisika hampir tak punya tempat apapun dan hampir direduksi menjadi penegasan keesaan absolut Tuhan, berlawanan dengan ide Bapak dan Putera dalam Kristen. Di sisi lain, aturan perilaku dan anjuran moral terdapat di setiap langkah, dalam berbagai bentuk tuntunan, dongeng, dan perumpamaan. Jika kita mengikuti perkembangan Islam, di Timur maupun Barat, kita pasti melihat kelemahan ekstrim filosofi Muslim, bila dibandingkan dengan peran penting yang metafisika mainkan di kalangan bangsa Yunani dan bangsa India periode Brahmanik. Barangkali kita mesti menisbatkan kemiskinan saintifik agama-agama berbasis al-Qur’an lebih kepada fitrah akal Semitik—yang inferior dalam hal sains dibanding kejeniusan bangsa-bangsa Arya—ketimbang kepada karakter moral revolusi Muslim. Opini ini, yang sudah lama berlaku di kalangan terpelajar, semakin terkonfirmasi setiap harinya dan cenderung menjadi poin yang tak terbantahkan. Bahkan, adalah pasti bahwa hampir tidak ada filsafat teoritis di dalam kitab-kitab Semit yang mendahului al-Qur’an, dengan kata lain di dalam Alkitab dan tulisan-tulisan Ibrani lain. Jika tidak ada agama lain di depan mata kita selain agama-agama yang dideduksikan dari agama Musa, maka kita tidak bisa menegakkan hukum yang menunjukkan agama-agama yang mampu berkarakter praktis hanya setelah mereka—boleh dibilang—asing dengan moralitas; tapi sudah pasti agama-agama murni Arya dikembangkan menurut hukum tersebut.
Selama berabad-abad, Buddhisme di India tetap campuraduk, terkait bagian metafisikanya, dengan mazhab-mazhab Brahmanik tertentu. Kemudian, ketika ia berpisah dari mereka, yakni ketika ia meninggalkan India, dan mulai menyebar di Tibet, Sri Lanka, dan di kalangan bangsa-bangsa kuning, ia mempertahankan sebagian besar simbol-simbol Brahmaniknya, meski dengan beberapa modifikasi. Di sisi lain, Buddha, sedari awal, memperkenalkan diri kepada manusia sebagai pendiri sebuah doktrin moral yang didasarkan pada kebajikan dan kemurahan. Ketika murid-muridnya berkumpul dalam majelis untuk mendirikan gereja Buddhis primitif, tujuan tunggal yang mereka hendak capai bukanlah untuk mengajari manusia metafisika baru, tapi untuk mengubah moral mereka yang buruk, untuk membebaskan pikiran/budi dari nafsu-nafsu yang merendahkannya, dan untuk mempersatukan mereka kembali dalam sentimen kasih universal. Dari sini lahirlah proselitisme itu, abnegasi tanpa ukuran itu, yang mengubah para rasulnya menjadi pemberadab kaum-kaum barbar, contohnya kaum Tibet dan semenanjung Trans-Gangga. Kaum-kaum ini tetap metafisikawan yang sangat buruk, tapi tatakrama mereka telah diperlembut; dan mereka dapat menanggalkan dimulainya peradaban mereka dari Buddhisme. Dari sini pulalah lahir semangat perbauran keagamaan yang telah mengadakan kekaisaran yang begitu besar di Timur untuk gereja-gereja Buddhis, yang telah menjadikan
dakwah sebagai salah satu tugas pertama pendeta, yang menjadikan kaul sebagai praktek biasa, dan yang, dengan mendorong banyak manusia untuk membidik moralitas yang hampir mustahil, telah memadati satu seksi Asia dengan biara-biara, dan memperlihatkan kepada kita hari ini kota-kota padat penduduk yang seluruhnya tersusun dari biara-biara.
Tidak seperti Buddhisme, Brahmanisme sama sekali tidak memberikan universalitas tersebut kepada institusi moralitas. Memang benar, di masa sangat kuno, kita melihat para Brahmana yang meredaksi hukum Manou menyibukkan diri dengan perilaku manusia; tapi kitab ini, yang merupakan kitab undang-undang para Brahmana, lebih bertujuan pada pematokan dasar konstitusi sosial dan organisasi politik India, ketimbang pada penuntunan semua manusia (tanpa pembedaan kasta-kasta dan ras-ras) di jalan kebajikan. Hukum Manou tidak menuntut itu banyak-banyak dalam kasus manusia-manusia berkondisi inferior; itu lebih keras untuk para bangsawan dari kasta kerajaan; tapi itu membebankan kemurnian dan kesempurnaan moral pada pria dan wanita dari kasta pendeta saja. Di sisi lain, metafisika menduduki tempat penting dalam hukum Manou; subjek ini saja menempati hampir seisi kitab pertama dan terakhir tersebut. Terdapat lebih banyak teori dalam satu volume Sanskerta tersebut dibanding dalam seluruh literatur Buddhis.
Mari kita mundur lebih jauh ke masa lalu. Veda-veda mendahului Brahmanisme, dan memberinya titik keberangkatan. Nah, moralitas tidak memiliki tempat sama sekali di dalam kidung-kidung Veda. Oleh karenanya, pasti dalam selang waktu antara periode tersebut (yang memanjang beberapa abad) dan pendirian konstitusi Brahmanik, pasti dalam selang waktu inilah orang-orang Arya Tenggara mulai mendeduksikan dari doktrin-doktrin mereka konsekuensi moral yang benihnya mereka kandung. Brahmanisme, yang datang sesudahnya, memupuk benih-benih primitif ini, dan merumuskan praktek-praktek purba sampai taraf tertentu; tapi ia tak pernah melupakan keanekaragaman kasta, bakat, dan fungsi. Baru pada abad 6 SM-lah dakwah-dakwah Buddhis memberikan karakter universalitas miliknya kepada moralitas praktis, dan dari karakter itu mereka membuat sebuah hukum untuk semua umat manusia.
Sementara peristiwa-peristiwa ini sedang berlangsung di Timur, bangsa-bangsa kuno ras Arya, bangsa Yunani, bangsa Latin, bangsa Jerman, belum keluar dari periode Vedik dan belum mengalami revolusi moral seperti bangsa-bangsa India. Ketika kita sekarang berusaha mengenali bagian moral dari agama-agama yang disebut pagan, kita terheran menjumpai sebuah negasi. Sudah pasti, di kalangan bangsa Yunani, bukan ajaran agama mereka yang menyediakan aturan hidup, dan memberi wawasan kebajikan, melainkan para filsuf mereka. Kehidupan para filsuf ini, sebagaimana kita dengar dari Diogenes Laertius, membuktikan bahwa sebagian besar filsafat Yunani, khususnya moralitas, datang dari Timur, ke mana kaum terpelajar telah pergi untuk mencarinya. Adapun agama, itu tetap sebuah institusi publik, yang dengannya banyak praktek individual dikelompokkan; tapi satu-satunya nilai riilnya terdapat dalam simbolisme metafisik yang berfungsi sebagai sebuah fondasi untuknya. Ketika Kristen menembus ke dunia Barat, ia-lah yang pertama mendakwahkan moralitas atas nama agama, dan yang menjadikan aturan hidup sebagai bagian dari ajaran dogma. Orang-orang Kristen mencela agama Pagan, bahwa itu bukan hanya asing dengan moralitas, tapi seringkali bahkan menentang moralitas dengan mencontohkan keasusilaan kepada manusia. Oleh karenanya, Kristen tidak didahului oleh moralitas apapun di kalangan bangsa-bangsa Barat; adalah upaya sia-sia, selain sama sekali tak ilmiah, untuk menunjukkan bahwa seluruh moralitas Kristen dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para filsuf Yunani atau Latin sebelum masa Yesus Kristus. Tidak ada yang mengagetkan dalam fakta—dan aku tidak mengerti kenapa ini sampai tidak diakui—bahwa para moralis Kristen sejak awal meniru dari disertasi-disertasi para filsuf; tapi, jikapun ini terbukti, faktanya tetap bahwa Kristen adalah sebuah revolusi moral di Barat yang meluas ke semua manusia, dan sebuah revolusi yang berproses melalui agama, dan bukan melalui filsafat. Ini adalah poin nyata. Sudah pasti, sebelum Kristen, tak pernah ada di dunia Barat sebuah pendidikan moral dan populer yang hadir dalam bentuk agama, dan menjadi bagian dari sebuah kredo. Oleh karenanya, agama tersebut pada mulanya memiliki karakter sebuah revolusi moral. Kemudian, menjelang akhir abad kedua, ia mulai mengembangkan metafisikanya, yang, dalam diskusi para bapa dan filsuf Alexandria, mencapai ketinggian yang sebelumnya dicapai oleh murid-murid Plato dan murid-murid Timur; tapi apapun dulu dan apapun nanti nilai penting metafisika Kristen, pengaruh sejati Kristen dan kebesaran sejatinya terletak dalam aksi moral yang dijalankannya.
Dengan demikian, semakin jauh kita mundur ke belakang dalam rangkaian zaman, semakin kita melihat di kalangan kaum-kaum Arya sebuah agama yang berbeda dari moralitas. Dan ketika kita sampai pada Veda-veda, atau politeisme bangsa-bangsa Barat, kita menemukan di dalam agama hanya dua elemen esensialnya—Tuhan dan pemujaan.
Penyisihan yang sama terjadi dalam kasus sepadan, yaitu kependetaan. Tidak ada sistem sosial di mana golongan pendeta/imamat dikonsolidasi ke dalam hirarki yang begitu kokoh kecuali dalam tiga agama modern, Islam, Kristen, dan Buddhisme. Kependetaan Brahmanik berutang keawetannya bukan kepada pengangkatan khususnya, yang mana tidak ada, melainkan kepada rezim kasta, di mana pendeta boleh dibilang adalah dasarnya. Semua Brahmana adalah setara, dan sejak awal tidak pernah mengakui satupun dari mereka sebagai ketua. Kesamaan awal mereka, yang digambarkan dengan mulut Brahma, menjadikan mereka independen dari satu sama lain; tak satupun dari mereka bisa membebankan kewajiban atau memberikan perintah kepada yang lain; jika seorang Brahmana memperoleh kewenangan yang belum diperoleh oleh yang lain, dia berutang itu kepada ilmunya, dan bukan kepada keunggulan fungsi apapun. Kesetaraan hirarki pendeta ini menghasilkan kebebasan berpendapat; jika ada yang namanya ortodoksi di India, yang menentukannya bukanlah kewenangan seorang ketua atau dewan Brahmana apapun, melainkan semata-mata kesesuaiannya dengan Veda, yakni Kitab Suci. Alhasil, selalu ada ruang untuk pembahasan poin doktrin apapun, tanpa kemungkinan dituduh atau dihukum oleh kekuasaan gerejawi apapun; kebebasan berpikir adalah mutlak di kasta pendeta. Jika kita mundur ke sebelum zaman Brahmanik, kita tidak menemukan jejak kependetaan yang diangkat secara reguler, atau pendeta apapun sama sekali; tidak ada lagi pendeta-pendeta yang dibedakan dari manusia lainnya; setiap bapak sebuah keluarga adalah pendeta pada saat dia menunaikan fungsi sakral tersebut, sebagaimana dia adalah tentara dalam perang dan buruh di ladang. Baru menjelang akhir periode Vedik-lah kita melihat fungsi kependetaan jadi terpancang pada keluarga-keluarga tertentu, sebagaimana wewenang kerajaan dan kekuasaan militer jadi terpancang pada keluarga-keluarga tertentu lain; tapi sebelum masa itu komunitas Arya tersebut telah membentuk konsepsi dewa-dewanya, dan mempraktekkan ritus-ritusnya, tanpa aksi perantara organisasi kependetaan apapun.
Membaca
Illiad-nya Homer dengan teliti akan menunjukkan kepada kita keadaan yang sama di kalangan bangsa Yunani. Ada pekurban-pekurban yang dipekerjakan di kuil-kuil tertentu, yang kadang mewariskan fungsi sakral ini kepada anak-anak mereka; tapi, berdampingan dengan mereka ini, upacara-upacara paling sering ditunaikan oleh tangan-tangan yang memegang pedang, dan doa dipanjatkan oleh mulut yang sesaat kemudian meninggikan seruan perang. Agamemnon adalah prajurit, hakim, atau pekurban, tergantung keadaan. Fungsi kependetaan kala itu belum memiliki keseksamaan yang diperolehnya belakangan; dan jika kita mendapati itu begitu kurang didefinisikan di masa puisi-puisi Homer, bukankah kita semestinya menduga itu, pada zaman sebelumnya, adalah seperti yang kita dapati dalam kidung-kidung Veda paling kuno? Perkembangan kependetaan berlangsung sedikit demi sedikit di India; bermula dari garisbesar yang kita temukan dalam kidung-kidung, itu mengambil bentuk sebuah kasta di dunia Brahmanik; lalu dalam Buddhisme kasta mengalah pada hirarki kuat, yang mana Thailand, Sri Lanka, Tibet, dan China adalah contohnya. Di Barat, menggantikan lemahnya kependetaan Yunani, yang tidak bertumpu pada kasta ataupun hirarki, tiba-tiba naiklah organisasi gereja Kristen, sebuah organisasi yang bakal kita duga dimodelkan dari organisasi pendeta Buddhis, andai kita tidak tahu bahwa ia mengambil sebagai modelnya (sampai taraf tertentu) jenis agama politik di mana kaisar Romawi adalah paus berdaulatnya, dan bahwa ia muncul karena kebutuhan akan persatuan yang dirasakan oleh masyarakat Kristen sewaktu masih berupa komunitas rahasia dan sering dipersekusi. Kita tak perlu menggambarkan apa yang bisa dilihat oleh seluruh dunia; gereja-gereja Kristen, dan terutama gereja Katolik, menghadirkan sebuah kependetaan yang hirarkinya terus memperkuat diri dari tahun ke tahun, sejauh otoritas kepalanya diakui sebagai sumber tunggal semua kekuasaan sakral.
Jadi, moralitas dan kependetaan, dua bagian penting dari agama modern, terlihat semakin kecil seiring kita menanjaki rangkaian abad. Pada akhirnya tidak ada lagi yang tersisa, sebagai elemen esensial agama-agama, selain satu fakta intelektual, yakni dogma, dan satu aksi eksterior, yakni pemujaan.
Berhubung sains dogma dan pemujaan hanya bisa diciptakan dengan menanjaki aliran tahun, itu pasti memerlukan keadaan terkini agama-agama sebagai titik keberangkatannya. Bab pertama dari sains ini adalah pemaparan sederhana hal-hal yang eksis, bab kedua adalah bagian sejarah. Nah, fakta-fakta yang ada jelas hanya bisa menemukan penjelasan dalam fakta-fakta yang belum lama mendahului mereka, dengan kata lain, jika kita tidak menganggap sejarah umat manusia sebagai serangkaian mukjizat tanpa putus, yang mana berlawanan dengan sains. Nalar manusia, yang direduksi ke bentuk paling sederhananya oleh psikologi modern, merupakan dasar dari tiada lain ide Tuhan; hanya saja ide tersebut hanya dapat dipahami dengan jelas melalui serangkaian analisa, yang menyisihkannya sedikit demi sedikit dari medium sekitarnya. Analisa-analisa ini tidak dilakukan dalam sehari; sebaliknya, mereka memakan banyak waktu; setiap filsuf melakukannya sendiri, berdasarkan metode-metode yang dipahami dengan baik, tapi umat manusia perlu berabad-abad untuk memahami analisa paling sederhana. Di setiap langkah yang diambilnya, umat manusia menyadari definisi Tuhan yang lebih tepat daripada sebelum-sebelumnya, yang tapi tidak bakal mereka capai, jika yang lain tidak mendahului. Orang yang tidak mengakui prinsip ini tidak bisa memahami sejarah agama-agama, yang mana disubordinasikan, seperti segala sesuatu di dunia ini, pada hukum suksesi dan koneksi. Satu penemuan tidak bisa dibuat, kecuali sebagai akibat dari satu penemuan sebelumnya, yang terikat padanya seperti api membara terikat pada cetus api yang menyalakannya. Ide Tuhan melintasi abad-abad, pada dasarnya hampir identik, tapi menerima tambahan-tambahan yang senantiasa segar dalam pengekspresiannya. Dewa-dewa dalam kidung-kidung Vedik tidak lagi menjelaskan ide Tuhan yang kita miliki sekarang, kendati mereka dipuja selama berabad-abad, dan kendati pada waktu itu para penyair menganggap mereka jauh lebih unggul daripada yang dipuja sebelumnya. Tuhan materil dari pasal-pasal pertama Kitab Kejadian hampir tidak memiliki kesamaan dengan Tuhannya orang Kristen, yang berupa roh murni dan sempurna. Meski demikian, para metafisikawan paling terpelajar dari timur mengakui Veda sebagai fondasi doktrin-doktrin mereka. Pada Kejadian, orang-orang Kristen menyaksikan kitab paling kuno di antara kitab-kitab suci mereka, dan darinya, secara tradisi, mereka menerima gagasan Tuhan. Maka jelas—di sini agama cocok dengan sains—bahwa kepercayaan hari ini menemukan sebab eksistensinya dalam kepercayaan hari kemarin, dan bahwa, dalam rangka mengkonstruksi sains dogma-dogma, kita harus menelusuri semua anak tangga yang sudah umat manusia lalui; tapi tambahan-tambahan berturutan pada konsepsi dan institusi keagamaan tidak bisa dijelaskan, kecuali jika kita selalu memiliki, di depan mata kita, dasar metafisik yang menyusun nalar manusia.
Tetap saja, sains agama-agama jauh dari sains para filsuf. Sains para filsuf bergerak jauh lebih cepat dan seperti berlari tunggang-langgang jika dibandingkan dengan defile dogma-dogma suci yang lambat dan tanpa putus. Sistem-sistem filosofis merupakan karya orang-orang terpelajar, dan tidak melangkah ke luar lingkaran sempit yang terdiri dari segelintir orang yang mencurahkan diri pada meditasi; sistem-sistem ini hanya menjawab kebutuhan spiritual, dan jarang memiliki perhatian apapun pada kehidupan nyata. Gerakan-gerakan keagamaan besar mempengaruhi masyarakat yang literer dan yang tidak; mereka mengagitasi massa populer dan menggerakkan sentimen-sentimen yang menjiwai massa populer. Revolusi filosofis hanyalah mainan anak kecil jika dibandingkan dengan revolusi keagamaan. Ilmu tentang yang satu tidak bisa menjadi ilmu tentang yang satu lagi.
Tapi, lantaran para filsuf hidup di dalam sanubari masyarakat keagamaan, entah mereka percaya pada dogma-dogmanya atau tidak, pertanyaan-pertanyaan yang mereka renungkan memiliki gaung di medium tempat mereka hidup; solusi-solusi yang mereka usulkan menerobos orang-orang selama konsekuensi praktis yang mengalir dari solusi itu menarik banyak orang. Sudah pasti Sokrates, Plato, ataupun Aristoteles tidak menjalankan pengaruh langsung pada bangsa Yunani di zaman mereka; tapi opini mereka, yang menyebar sedikit demi sedikit, lambat-laun mengasingkan orang-orang dari politeisme, dan mempersiapkan kejatuhannya. Memakan berabad-abad untuk penuntasan tersebut, dengan cara ini. Jumlah total ide-ide individual menghasilkan kredo sebuah kaum; ide-ide ini sendiri dihasilkan melalui aksi-aksi kompleks, sangat kecil, dan bervariasi dalam seribu cara. Ketika jumlah total ide-ide baru melampaui jumlah total ide-ide yang menyusun keyakinan khalayak, keseimbangan terganggu, keyakinan khalayak memberi tempat, dan menghilang sedikit demi sedikit. Kita tidak boleh menyangka bahwa paganisme digantikan secara langsung oleh agama Kristus. Agama ini menaiki singgasana kerajaan selama lebih dari dua ratus tahun, tapi kurban-kurban masih dipersembahkan kepada para dewa di banyak kuil Yunani; dan kita sendiri tahu, di negeri tersebut, bahwa banyak santo dan tokoh Kristen baru berhasil menggantikan dewa-dewa kuno dengan mengadopsi nama yang serupa atau dengan menjadi objek pemujaan yang sepadan. Tak terhitung jejak-jejak agama-agama kuno masih eksis di dalam sanubari Kristen, yang tak pernah berhasil menghapus mereka sepenuhnya. Semua fakta yang dikumpulkan di zaman belakangan, di Jerman maupun Prancis, membuktikan bahwa agama-agama tidak menghasilkan tabula rasa ketika mereka menggantikan satu sama lain, tapi bahwa mereka saling mempenetrasi dengan suatu cara, seperti dua bentuk berturutan dari seekor serangga yang mengalami metamorfosa; bentuk baru menggantikan bentuk kuno setahap demi setahap, dan hanya melepaskan diri secara penuh pada waktunya.